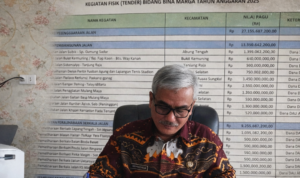Pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) di Indonesia sejatinya berada dalam koridor sistem merit. Regulasi mengamanatkan proses yang objektif, transparan, dan profesional. Namun, di balik mekanisme formal itu, kontestasi menuju jabatan tertinggi dalam birokrasi daerah kerap dihiasi dinamika non-formal yang tak jarang menyerupai “perang psikologi”.
Istilah ini bukanlah konsep resmi, melainkan gambaran dari serangkaian manuver politik yang berupaya membentuk opini, mempengaruhi pengambil keputusan, hingga menguji ketahanan mental para kandidat.
Pada fase-fase krusial seleksi, informasi kerap menjadi senjata. Rekam jejak kandidat disorot, tetapi tak jarang informasi dilebih-lebihkan, dipelintir, atau dipakai untuk membangun atau meruntuhkan citra. Media massa, media sosial, hingga jaringan birokrasi menjadi ruang pertempuran opini.
Isu yang diangkat berkisar pada integritas, kedekatan politik, hingga dugaan konflik kepentingan. Kampanye senyap ini menciptakan tekanan bagi para kandidat untuk menjaga reputasi sekaligus meredam rumor yang bisa berubah menjadi bola salju.
Meskipun panitia seleksi bekerja berdasarkan aturan, tarik-menarik kepentingan politik tak sepenuhnya bisa dihilangkan. Dorongan dari kepala daerah atau kekuatan partai tertentu bisa menempatkan kandidat dalam posisi dilematis.
Mereka yang dinilai “terlalu independen” menghadapi tekanan agar menyesuaikan diri. Sementara kandidat yang dianggap dekat dengan kekuasaan dikejar isu keberpihakan. Situasi ini menghadirkan ketegangan yang menggerus kenyamanan psikologis selama proses berjalan.
Ketika kelompok masyarakat sipil, akademisi, atau pihak yang dirugikan mempertanyakan transparansi proses, tekanan berbalik kepada panitia seleksi. Tuntutan agar penilaian dibuka, metode diuji, dan hasil diperjelas, menjadi bentuk kontrol publik.
Keraguan terhadap kredibilitas proses seleksi bukan hanya menekan panitia, tetapi juga memengaruhi persepsi para kandidat terhadap peluang mereka sendiri.
Dalam situasi penuh persaingan, kekuatan jejaring menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Lobi dianggap sebagai bagian tak tertulis dari dinamika birokrasi. Dukungan tokoh, rekomendasi informal, hingga komunikasi non-protokoler dapat ikut mempengaruhi atmosfer kompetisi.
Bagi sebagian kandidat, absennya jejaring kuat menciptakan tekanan tersendiri, sementara mereka yang didukung jaringan besar menghadapi ekspektasi yang sama besarnya.
Ada kalanya isu hukum muncul tiba-tiba, menyeruak di tengah proses seleksi. Baik berupa kasus lama yang diungkit kembali maupun dugaan baru yang belum terbukti. Walaupun tak selalu berujung pada proses hukum formal, dampaknya bisa signifikan: menggoyang kepercayaan publik dan menggembosi peluang kandidat.
Di tangan pihak tertentu, isu hukum kerap dijadikan strategi psikologis untuk melemahkan lawan.
“Perang psikologi” dalam pemilihan Sekda mencerminkan betapa strategisnya posisi ini dalam pemerintahan daerah. Di balik mekanisme seleksi yang terstruktur, terdapat dinamika persaingan yang bekerja dalam ruang-ruang tak kasat mata.
Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan semata memilih kandidat dengan nilai terbaik, melainkan memastikan proses berjalan bebas dari intervensi, sehingga sistem merit benar-benar menjadi panglima dalam birokrasi Indonesia.
Penulis: Syaiful Rahman