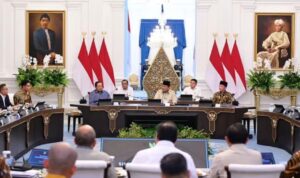Jakarta : Lebih dari empat dekade telah berlalu, namun bayang-bayang Operasi Petrus (Penembakan Misterius) masih menjadi salah satu bab paling gelap dalam sejarah Indonesia modern.
Operasi yang berlangsung senyap pada awal 1980-an ini tidak hanya meninggalkan jejak kematian, tetapi juga trauma, stigma, dan pertanyaan tentang keadilan yang hingga kini belum terjawab sepenuhnya.
Petrus bukan sekadar peristiwa kriminal, melainkan fenomena kekuasaan, ketika negara hadir secara tersembunyi, mematikan, dan tanpa mekanisme hukum yang transparan.
Operasi Petrus mulai mencuat ke ruang publik sekitar tahun 1982, pada masa pemerintahan Orde Baru. Saat itu, stabilitas keamanan menjadi agenda utama negara. Premanisme dan kriminalitas dipersepsikan sebagai ancaman serius terhadap ketertiban sosial dan pembangunan nasional.
Sejak periode tersebut, masyarakat di berbagai kota dikejutkan oleh penemuan mayat-mayat dengan luka tembak, umumnya di kepala atau dada. Jenazah ditemukan secara terbuka di pinggir jalan, sawah, sungai, hingga pasar. Tidak ada proses peradilan. Tidak ada penjelasan resmi.
Istilah “Petrus” lahir dari masyarakat sendiri, mencerminkan ketakutan terhadap sesuatu yang tidak terlihat, tetapi nyata dampaknya.
Bagi banyak warga, Petrus bukan hanya berita kriminal, melainkan teror psikologis kolektif. Ketakutan menyusup ke kehidupan sehari-hari. Orang-orang menjaga ucapan, menghindari konflik, dan memilih tidak bertanya.
Bagi keluarga korban, kehilangan tak hanya berarti duka, tetapi juga stigma. Mereka dipaksa diam, menanggung luka tanpa ruang keadilan dan pengakuan. Kesedihan mereka berlangsung dalam sunyi.
Korban Petrus umumnya dilabeli sebagai preman atau residivis, yang kala itu dikenal dengan istilah “Gali” (Gabungan Anak Liar Indonesia). Istilah ini merujuk pada kelompok informal penguasa wilayah jalanan pelaku pemalakan, penganiayaan, pengamanan ilegal, hingga kekerasan terbuka.
Ciri mereka mudah dikenali, dari tato, rambut gondrong, aksesoris logam, bahasa kasar, dan reputasi sebagai “jagoan lokal”. Dalam perspektif keamanan Orde Baru, mereka dianggap biang kekacauan sosial.
Namun berbagai penelitian dan kesaksian menunjukkan satu kenyataan penting, tidak semua korban Petrus memiliki catatan kriminal yang jelas. Yang pasti, seluruh korban kehilangan hak paling dasar. Hak hidup dan hak atas pengadilan yang adil.
Yogyakarta menjadi salah satu episentrum awal Petrus. Kota pelajar itu mendadak berubah mencekam. Penemuan mayat terjadi beruntun dengan pola nyaris seragam. Preman menghilang dari jalanan. Ketakutan membungkam percakapan publik.
Letkol M. Hasbi, Komandan Kodim 0734 sekaligus Kepala Staf Garnisun Yogyakarta saat itu, kemudian mengakui adanya keterlibatan militer dalam operasi penumpasan kejahatan. Namun identitas pelaku lapangan tetap misterius. Mereka dikenal sebagai “tim OPK”. Bergerak tanpa identitas, tanpa jejak administratif.
Teror Petrus meluas ke Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya, hingga Bandung dan sejumlah kota lainnya di Indoensia. Eskalasi signifikan terjadi setelah Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 1982 menegaskan perlunya tindakan keras terhadap kriminalitas.
Pada 19 Januari 1983, para petinggi keamanan termasuk Pangkopkamtib Laksamana Soedomo, Kapolri, Pangdam Jaya, dan Kapolda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi di Markas Kodam Jaya. Dari sinilah lahir Operasi Celurit, yang menjadi payung penumpasan kejahatan di kota-kota besar.
Hingga kini, jumlah korban Petrus tidak pernah diumumkan secara resmi oleh negara. Kekosongan data ini membuat angka korban hanya dapat diperkirakan berdasarkan laporan media, riset akademik, dan catatan organisasi masyarakat sipil.
Berbagai sumber menyebut
ratusan korban pada tahap awal,
hingga 1.000–3.000 orang selama keseluruhan operasi berlangsung.
Sementara dokumentasi tak resmi mencatat,
Tahun 1983: 532 orang tewas (367 akibat tembakan)
Tahun 1984: 107 orang tewas (15 akibat tembakan)
Tahu 1985: 74 orang tewas (28 akibat tembakan)
Perbedaan angka ini menunjukkan satu fakta pahit, banyak korban tidak pernah tercatat dalam sejarah resmi negara.
Sebagian korban ditemukan terikat, dimasukkan ke dalam karung, lalu dibuang di ruang publik. Metode ini disebut aparat sebagai shock therapy. Terapi kejut untuk menanamkan rasa takut.
Dalam buku Benny Moerdani yaitu Profil Prajurit Negarawan, Presiden Soeharto menjelaskan logika kebijakan tersebut, “Yang melawan, mau tidak mau harus ditembak… Itu untuk shock therapy, supaya orang tahu masih ada yang bisa bertindak terhadap kejahatan.”
Bagi sebagian masyarakat, cara ini dianggap efektif. Kejahatan menurun. Preman menghilang. Dukungan publik muncul dalam diam.
Namun bagi pemerhati HAM dan akademisi hukum, Petrus adalah eksekusi di luar hukum. Pelanggaran HAM berat yang meruntuhkan prinsip negara hukum.
Menjelang 1985, praktik penembakan misterius mulai berkurang. Namun tidak pernah ada pernyataan resmi tentang penghentian operasi. Petrus tidak berakhir secara formal, melainkan menghilang perlahan dari ruang publik.
Tak ada pengadilan. Tak ada pertanggungjawaban negara. Arsip tak pernah dibuka. Keluarga korban hidup dengan kehilangan tanpa kejelasan.
Operasi Petrus memang menekan kriminalitas dalam jangka pendek. Namun ia meninggalkan warisan trauma, ketakutan, dan krisis keadilan jangka panjang.
Pertanyaan mendasar itu masih menggantung hingga hari ini.
Apakah negara boleh membunuh demi ketertiban?
Mengenang Operasi Petrus bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk memastikan bahwa kekuasaan tak lagi berjalan tanpa hukum dan pengawasan. Sebab bangsa yang besar bukanlah bangsa yang melupakan sejarah kelamnya, melainkan bangsa yang berani mengingat dan belajar darinya.
(**/Dikutip dari berbagai sumber)